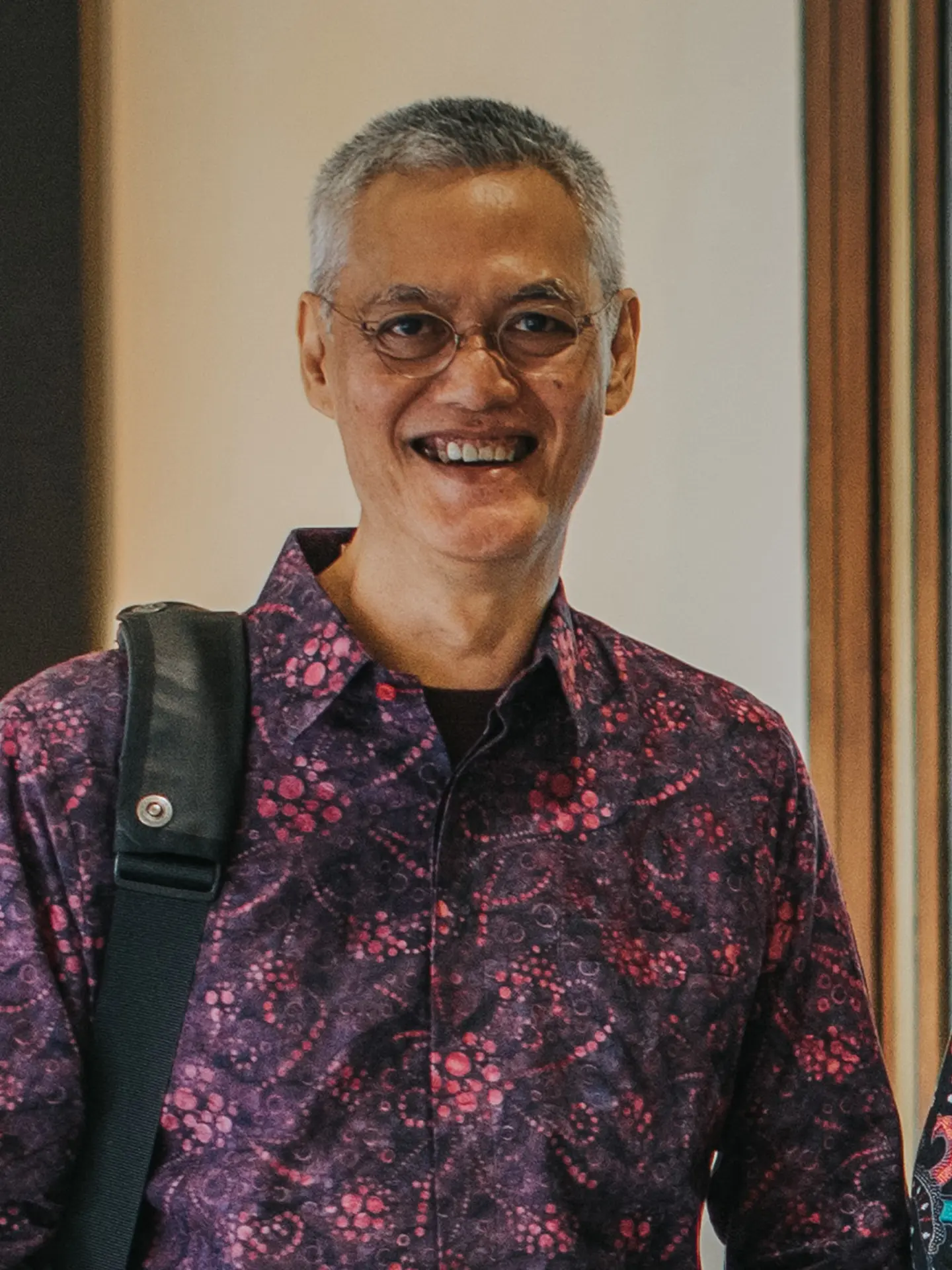Oleh:
Jalal – Chairperson of Advisory Board
Sonny Sukada – Senior Advisor
Social Investment Indonesia
Dalam dunia bisnis yang tengah menghadapi disrupsi besar-besaran—baik karena krisis iklim, ketimpangan sosial, maupun tekanan dari ‘kecerewetan’ investor global—konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjelma menjadi salah satu penentu daya saing perusahaan. ESG bukanlah sekadar indikator reputasi atau pemenuhan formalitas regulasi, tetapi, dalam maknanya yang paling luas, telah menjadi kerangka strategis untuk memastikan ketahanan (resilience), keberlanjutan (sustainability), dan pertumbuhan jangka panjang.
Di Indonesia, wacana ESG berkembang sangat pesat dalam lima tahun terakhir. Namun, seperti banyak negara berkembang lainnya, tantangannya bukan pada pemahaman konsep semata, melainkan pada penerapannya yang autentik dan terintegrasi di seluruh lini bisnis. Dan karenanya, pemahaman atas apa yang disebut sebagai integrasi ESG adalah penting dan urgen bagi dunia bisnis di Indonesia.
Integrasi ESG tidak bisa dimulai dari laporan atau program yang bersifat kosmetik. Ia menuntut perubahan mendasar dalam cara perusahaan memaknai risiko, nilai bahkan tujuan keberadaannya. Dengan kata lain, ESG bukan bolt-on, melainkan built-in. Perusahaan yang serius menerapkan ESG memahami bahwa keberlanjutan bukan sekadar moralitas atau etika dalam berbisnis, tetapi rasionalitas ekonomi jangka panjang. Investasi pada dekarbonisasi, efisiensi sumberdaya, atau kesejahteraan pekerja, misalnya, bukan beban biaya, melainkan investasi jangka panjang dalam daya tahan dan reputasi perusahaan.
Jadi, apa yang disebut sebagai integrasi ESG oleh perusahaan? KPMG, CLP dan CS dalam dokumen Integrating ESG into Your Business mungkin menyediakan jawaban terbaik bagi siapapun yang ingin mengetahui langkah demi langkah integrasi ESG di dalam perusahaan. Namun, sebagai dokumen yang sudah berusia 5 tahun, perkembangan yang sudah sangat pesat agaknya membuat dokumen tersebut perlu untuk ditinjau ulang dan diperbaiki. Di sini, kami mengusulkan empat fase integrasi ESG ke dalam bisnis yang disandarkan pada dokumen tersebut, namun dilengkapi dengan berbagai perkembangan mutakhir agar bisa menjawab kebutuhan sekarang hingga beberapa tahun ke depan.
Fase I: Fondasi dan Penyelarasan Nilai
Tahap pertama dalam integrasi ESG adalah membangun fondasi organisasi yang kuat. Fase ini mencakup upaya level setting—membangun kesamaan pemahaman tentang apa itu ESG dan mengapa ia penting bagi keberlanjutan bisnis. Banyak perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN dan perusahaan publik, masih terjebak pada pemaknaan ESG sebagai kepatuhan terhadap peraturan OJK atau penegakan GCG semata. Padahal, inti dari ESG adalah menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan serta risiko sosial dan lingkungan, yang pada akhirnya untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
Kunci utama dalam fase ini adalah tone at the top. Komitmen ESG tidak akan hidup tanpa dukungan eksplisit dari dewan komisaris dan direksi. Mereka semua harus menjadi champion yang menanamkan filosofi keberlanjutan ke dalam visi perusahaan. Ketika visi keberlanjutan menjadi bagian dari tujuan luhur perusahaan (corporate purpose), maka arah kebijakan, investasi, dan pengambilan keputusan akan bergerak selaras. Hal ini terlihat pada beberapa perusahaan besar Indonesia yang telah mengintegrasikan ESG dalam strategi korporasi yang mulai memandang transisi energi dan inklusi digital sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang.
Namun, fondasi nilai saja tidak cukup tanpa kapabilitas organisasi yang memadai. ESG literacy—kemampuan memahami konsep, metrik, dan dampak ESG—masih menjadi kendala serius di berbagai sektor. Perusahaan perlu berinvestasi pada pelatihan berkelanjutan, menciptakan posisi khusus seperti Chief Sustainability Officer (CSO), dan membentuk ESG Committee di tingkat dewan komisaris, dan ESG Executive Committe yang benar-benar lintas-fungsi untuk memastikan bahwa kebijakan keberlanjutan tidak hanya dilaksanakan oleh divisi CSR dan/atau lingkungan. Hanya dengan keselarasan dewan komisaris, direksi, dan eksekutif serta kolaborasi antara bagian keuangan, SDM, hukum, dan operasi, ESG dapat benar-benar menjadi denyut jantung organisasi.
Fase II: Diagnosis Strategis dan Alokasi Modal
Setelah fondasi terbentuk, langkah berikutnya adalah melakukan diagnosis strategis melalui materiality assessment. Penilaian materialitas memungkinkan perusahaan mengidentifikasi isu ESG yang paling relevan dengan model bisnis dan para pemangku kepentingannya. Pendekatan double materiality menjadi penting di sini: bukan hanya menilai bagaimana isu ESG memengaruhi nilai finansial perusahaan, tetapi juga bagaimana aktivitas perusahaan memengaruhi masyarakat dan lingkungan.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini memiliki dimensi yang unik. Misalnya, bagi perusahaan kelapa sawit, isu deforestasi dan hak pekerja merupakan materialitas sosial dan lingkungan yang utama. Sementara bagi sektor perbankan, eksposur terhadap pembiayaan yang tinggi karbon menjadi isu kritis. Pendekatan materialitas juga harus bersifat dinamis—isu yang tampak kecil hari ini bisa menjadi signifikan besok, seperti risiko transisi energi, dampak Kecerdasan Buatan terhadap tenaga kerja, atau perubahan regulasi terkait dekarbonisasi.
Hasil dari penilaian materialitas inilah yang menjadi dasar strategi ESG perusahaan. Strategi yang baik tidak hanya fokus pada mitigasi risiko, tetapi juga pada eksplorasi peluang. Misalnya, perusahaan manufaktur dapat menggunakan prinsip-prinsip ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah sekaligus menekan biaya produksi. Sektor energi dapat berinvestasi dalam teknologi rendah karbon untuk memanfaatkan pasar kredit karbon domestik yang kini berkembang pesat. Strategi semacam ini bukan hanya mengamankan perusahaan dari ancaman eksternal, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru yang selaras dengan nilai sosial dan lingkungan.
Yang tak kalah penting adalah penyelarasan strategi ESG dengan kerangka global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs memberi arah bagi perusahaan dalam mengukur kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat legitimasi sosial mereka. Di Indonesia, pemerintah mendorong integrasi ESG ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan peta jalan ekonomi hijau, yang menjadikan keberlanjutan sebagai agenda nasional.
Integrasi ESG juga harus meluas ke seluruh rantai nilai—bukan hanya pada perusahaan inti. Tantangan besar muncul ketika perusahaan bergantung pada jaringan pemasok kecil dan menengah yang belum siap menerapkan standar keberlanjutan. Banyak UKM belum memiliki sistem pelaporan yang memadai, atau bahkan pemahaman tentang emisi, limbah, dan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Karena itu, perusahaan besar perlu mengambil peran aktif melalui capacity building bagi pemasok—misalnya dengan menyediakan panduan praktik ESG, pendampingan teknis, hingga insentif bagi kinerja yang baik. Pendekatan kolaboratif semacam ini benar-benar membantu menciptakan shared value di seluruh ekosistem bisnis, sekaligus memerkuat daya saing nasional.
Fase III: Implementasi, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko
Tahap implementasi menuntut tata kelola yang kuat. ESG tanpa struktur tata kelola yang jelas hanya akan menjadi jargon. Dewan komisaris dan direksi harus menetapkan mandat pengawasan ESG secara formal, memastikan pembahasan rutin dalam rapat strategis, dan menghubungkannya dengan sistem insentif eksekutif. Skema ESG-linked bonus atau remunerasi berbasis target keberlanjutan merupakan salah satu praktik terbaik global yang mulai diadopsi di Indonesia. Sudah lama di sektor pertambangan bonus dikaitkan dengan kinerja K3, dan sudah saatnya diluaskan kaitannya dengan kinerja-kinerja ESG lainnya—demikian pula di sektor-sektor bisnis lain. Dengan mengaitkan kinerja ESG pada kompensasi, perusahaan menanamkan tanggung jawab keberlanjutan ke dalam mekanisme manajerial yang nyata.
Manajemen risiko juga harus diperluas untuk mencakup risiko ESG secara komprehensif. Kerangka Enterprise Risk Management (ERM) yang telah lama digunakan di sektor keuangan kini perlu diperbarui agar memasukkan risiko iklim fisik (seperti banjir atau kekeringan), risiko transisi (perubahan regulasi dan teknologi), serta risiko reputasi akibat praktik bisnis yang tidak etis. Analisis skenario dan stress testing berbasis iklim yang direkomendasikan oleh Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) menjadi alat penting untuk menguji daya tahan perusahaan dalam jangka panjang. Adopsi atau adaptasi rekomendasi Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) yang sangat penting untuk mengelola risiko keanekaragaman hayati juga tak kalah, dan akan semakin, penting.
Indonesia, sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim dan keanekaragaman hayati yang terus tergerus, harus menempatkan analisis semacam ini di pusat perencanaan korporasi. Bencana iklim dan menghilangnya keanekaragaman hayati tidak lagi sekadar risiko lingkungan, melainkan ancaman bisnis yang dapat memengaruhi aset, pasokan energi, dan rantai pasok bagi bisnis. Karena itu, perusahaan di sektor energi, pertanian, dan infrastruktur perlu memerkuat sistem peringatan dini dan diversifikasi pasokan sebagai bagian dari mitigasi risiko ESG.
Selain tata kelola dan risiko, infrastruktur data menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi ESG. Salah satu kelemahan mendasar banyak perusahaan di Indonesia adalah ketergantungan pada pengumpulan data manual dan spreadsheet yang seringkali sama sekali tidak terintegrasi. Akibatnya, data ESG sering tidak konsisten, sulit diverifikasi, dan tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan strategis. Penerapan sistem digital terintegrasi seperti platform GRC (Governance, Risk, and Compliance) atau perangkat lunak ESG khusus dapat membantu mengatasi masalah ini. Lebih jauh, pemanfaatan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), big data, dan blockchain dapat meningkatkan keandalan data, mendeteksi pola risiko secara real-time, serta memastikan transparansi rantai pasok.
Fase IV: Akuntabilitas, Pelaporan, dan Komunikasi
Tahap terakhir dalam integrasi ESG adalah membangun sistem akuntabilitas yang transparan dan kredibel. Perusahaan harus menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur, berbasis sains, dan berorientasi pada dampak. Inisiatif global seperti Science Based Targets initiative (SBTi) memberi panduan bagi perusahaan untuk mengembangkan target pengurangan emisi yang konsisten dengan komitmen global terhadap Persetujuan Paris. Namun, indikator ESG tidak boleh hanya mengukur output—seperti jumlah pohon ditanam atau pelatihan dilakukan—melainkan harus berfokus pada outcome, yakni perubahan nyata yang terjadi di masyarakat dan lingkungan, bahkan impact dalam jangka yang lebih panjang.
Pelaporan yang baik merupakan jantung dari kepercayaan. Pendekatan integrated reporting menjadi tren global karena mampu menjelaskan keterkaitan antara kinerja finansial dan non-finansial dalam satu narasi nilai. Laporan semacam ini menunjukkan bagaimana strategi ESG berkontribusi terhadap penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, sekaligus nilai sosial bagi masyarakat. Di Indonesia, regulator seperti OJK telah mewajibkan laporan keberlanjutan bagi perusahaan terbuka, namun tantangan terbesar terletak pada konsistensi dan kedalaman data. Oleh karena itu, melibatkan pihak ketiga independen untuk memberikan assurance atas laporan ESG menjadi langkah penting untuk meningkatkan kredibilitas dan mengurangi risiko greenwashing.
Namun pelaporan tidak boleh berhenti pada dokumentasi formal tahunan. ESG juga adalah tentang komunikasi yang hidup—sebuah dialog dua arah antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Komunikasi ESG harus dirancang secara strategis, jujur, dan berbasis bukti. Di satu sisi, perusahaan perlu mampu menceritakan kisah keberlanjutan mereka secara menarik agar dipahami publik dan investor. Di sisi lain, mereka juga harus terbuka terhadap kritik dan masukan untuk memerkuat kebijakan di masa depan. Komunikasi yang berlebihan tanpa dasar data yang kuat justru dapat memicu risiko reputasi, sementara keterbukaan yang disertai bukti nyata memerkuat kepercayaan dan loyalitas pemangku kepentingan.
Dari Kepatuhan Menuju Kepemimpinan
Indonesia sedang berada pada titik penting dalam evolusi keberlanjutan korporasi. Di satu sisi, regulasi dan tekanan pasar mendorong adopsi ESG secara cepat; di sisi lain, kapasitas dan kesiapan masih bervariasi antar-sektor juga antar-perusahaan. Namun justru di tengah transisi inilah peluang besar muncul. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan ESG secara autentik akan menjadi pemimpin masa depan—bukan hanya karena mereka bertanggung jawab, tetapi karena mereka tangguh dan relevan.
Integrasi ESG yang holistik, sebagaimana kerangka empat fasenya—fondasi nilai, diagnosis strategis, implementasi dan tata kelola, serta akuntabilitas dan komunikasi—menawarkan arah transformasi yang konkret. Ia membantu perusahaan menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, sekaligus menjembatani tujuan ekonomi dengan kepentingan sosial dan ekologis. Bagi Indonesia, penerapan ESG seharusnya bukan semata meniru praktik global, melainkan meneguhkan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan yang adil, tangguh, dan inklusif.
Masa depan bisnis Indonesia akan ditentukan oleh sejauh mana perusahaan mampu melihat ESG bukan sebagai kewajiban eksternal, tetapi sebagai inti dari strategi penciptaan nilai. Di era ketidakpastian global, hanya perusahaan yang berani menanamkan keberlanjutan ke dalam jantung operasinya yang akan bertahan, tumbuh, dan memberi arti bagi masa depan bangsa.
Jakarta, 10 November 2025
Penulis memanfaatkan mesin Kecerdasan Buatan (AI) untuk pencarian data serta penulisan kerangka dan draft awal. Tanggung jawab atas kebenaran informasi serta substansi pendapat tetap melekat pada penulis.